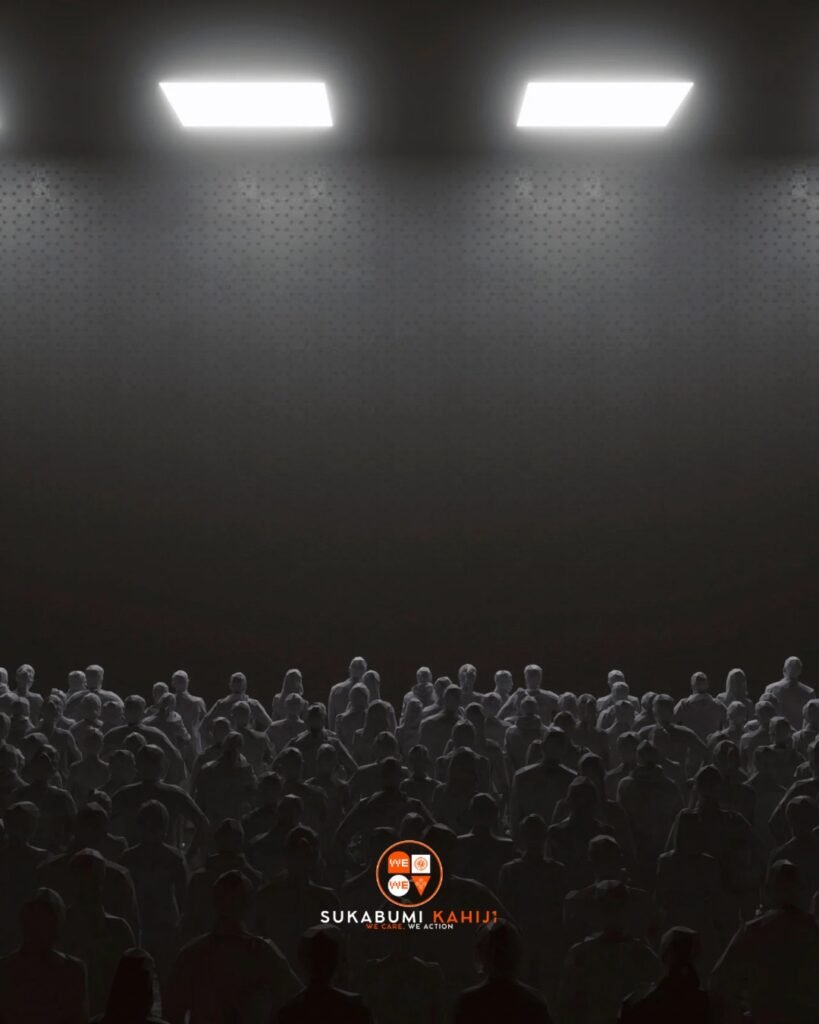Di tengah zaman yang serba cepat, ketika kebijakan diukur dari berapa viralnya dan kepemimpinan sering kali ditakar dari seberapa sering tampil di baliho, kita berisiko kehilangan sesuatu yang sangat mendasar.
Arah Politik, pada dasarnya, bukan soal siapa yang paling keras bicara atau paling banyak relasi, tapi soal siapa yang paling bisa menjaga makna.
Dari sini, saya memulai refleksi tentang bagaimana kita, khususnya di Kabupaten Sukabumi, bisa menawarkan politik yang tidak kehilangan jiwa.
Kita tidak bisa memisahkan kehidupan publik dari nilai. Dalam masyarakat yang masih menjunjung tinggi keluarga, tradisi, dan agama, pembangunan tak cukup hanya berbicara tentang jalan atau jembatan.
Ia harus bicara juga tentang manusia. Kita bisa membangun sekolah bertingkat, tapi jika anak-anak tak bisa membedakan antara benar dan salah, maka itu bukan kemajuan—itu kegagalan yang dibungkus rapi.
Di sinilah politik harus kembali menjadi panggilan nurani, bukan sekadar strategi meraih suara.
Pandangan ini sejalan dengan pemikiran Alasdair MacIntyre dalam bukunya After Virtue (1981). Ia menyebut bahwa masyarakat modern kehilangan kompas moral karena tidak lagi punya “narasi bersama” yang mengikat.
Politik jadi sekadar transaksi, bukan pertarungan nilai. Ini yang pelan-pelan juga terjadi di daerah. Maka penting bagi kita untuk tidak malu membicarakan soal kebaikan, soal akhlak, soal makna hidup—bahkan dalam ruang-ruang politik.
Dan dalam tradisi kita, hal itu bukan barang asing. Kita punya warisan pemikiran dari ulama seperti Buya Hamka yang dalam Tafsir Al-Azhar berulang kali menegaskan bahwa iman tidak cukup hanya diyakini; ia harus menampakkan dirinya dalam sikap adil dan pembelaan pada yang lemah.
Buya Syafii Maarif juga menulis hal serupa: “Agama bukan hanya urusan langit, tapi harus hadir dalam keadilan sosial di bumi.” (Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan, 2009).
Jadi bicara soal politik yang berpihak bukan berarti keluar dari peran keagamaan kita. Justru itulah intinya.
Dalam konteks Kabupaten Sukabumi, nilai-nilai itu masih hidup—meski sering kali terdesak. Kita melihat bagaimana para petani bertahan dengan cara hidup sederhana, bagaimana guru-guru honorer tetap mengabdi meski gajinya tak seberapa, dan bagaimana keluarga masih jadi benteng terakhir di tengah gempuran budaya instan.
Semua ini adalah modal sosial yang luar biasa, yang sayangnya jarang masuk dalam pembicaraan kebijakan. Kita perlu membalik arah: pembangunan harus mulai dari mereka yang paling sunyi, bukan dari gedung-gedung paling tinggi.
Michael Sandel, seorang filsuf dari Harvard, dalam bukunya Justice: What’s the Right Thing to Do? (2009), menulis bahwa masyarakat akan hancur jika pasar dan politik lepas dari nilai.
Itu sebabnya kita tidak bisa terus-menerus mengukur segalanya dari sisi ekonomi. Kalau ada lahan yang subur tapi ingin diubah jadi pabrik hanya karena nilainya lebih tinggi, itu bukan keputusan bijak. Itu keputusan yang putus hubungan dengan manusia dan tanah.
Begitu pula dengan pendidikan. Kita tidak sedang krisis gedung sekolah, kita sedang krisis makna belajar. Pendidikan kita terlalu sibuk mengejar angka—tanpa menyiapkan anak-anak jadi manusia utuh. Di sinilah kita harus kembali pada prinsip yang diajarkan Ki Hadjar Dewantara: mendidik itu membimbing jiwa, bukan hanya mengisi kepala.
Maka kebijakan daerah harus berpihak pada sekolah-sekolah yang menghidupkan karakter, bukan hanya yang terlihat megah.
Semua ini bukan sekadar romantisme. Ini adalah bentuk politik yang punya akar. Akar dari sejarah bangsa, dari agama, dari budaya, dari penderitaan orang kecil yang terlalu lama dianggap statistik.
Kalau politik bisa kembali berpijak di sana, maka ia akan jadi jalan pengabdian yang jujur. Kita bisa tidak sempurna, tapi kita tetap bisa berusaha setia pada nilai.
Referensi
1. Alasdair MacIntyre, After Virtue, University of Notre Dame Press, 1981.
2. Ahmad Syafii Maarif, Islam dalam Bingkai Keindonesiaan dan Kemanusiaan, Mizan, 2009.
3. Hamka, Tafsir Al-Azhar, Pustaka Panjimas, 1980.
4. Michael J. Sandel, Justice: What’s the Right Thing to Do?, Farrar, Straus and Giroux, 2009.
5. Ki Hadjar Dewantara, Pemikiran, Konsepsi, Keteladanan, Sikap Merdeka, Yogyakarta: Majelis Luhur Taman Siswa, 1962.